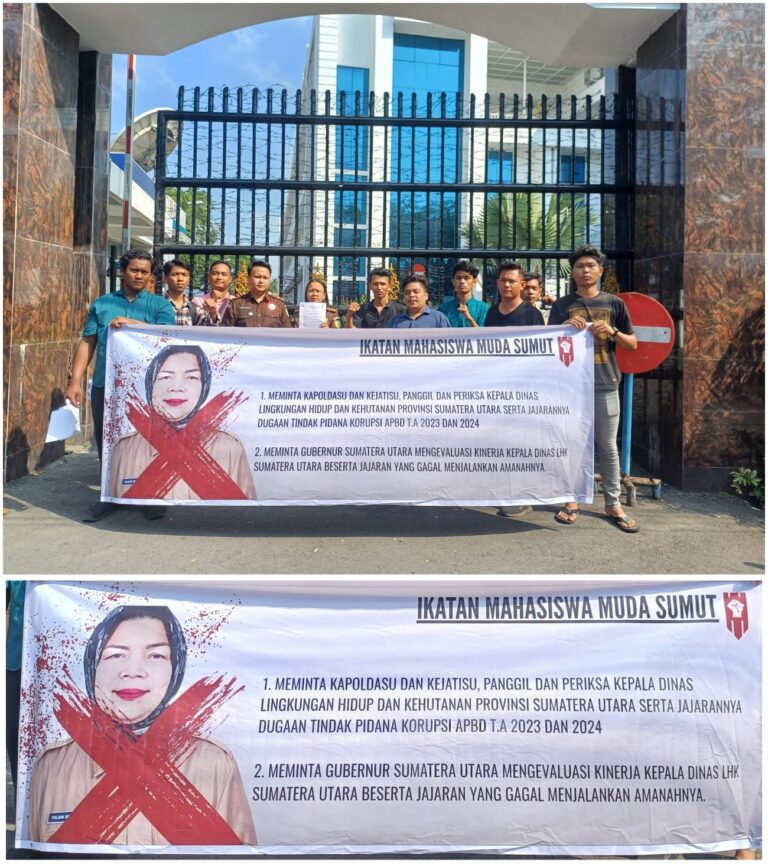Oleh : Tamara Rizki, BPH DPD IMM Sumatera Utara
Dia tidak bisa dikontrol, jadi lebih baik kita berhentikan kariernya.”
Pernyataan seperti ini mungkin pernah kita dengar entah sebagai bisikan dalam ruang-ruang rapat, sebagai percakapan informal di sudut-sudut organisasi, atau bahkan sebagai dasar keputusan yang terdengar “rasional” namun menyimpan luka kolektif yang mendalam. Esensinya tetap satu yaitu seseorang disingkirkan bukan karena ia tidak kompeten atau gagal menjalankan tugas, melainkan karena ia tidak tunduk, terlalu kritis, atau tidak sejalan dengan arus utama kekuasaan. Fenomena seperti ini dikenal luas sebagai cancel culture, sebuah gejala sosial yang pada awalnya meledak dalam ruang digital, namun perlahan menyusup ke dalam ruang-ruang sosial yang lebih sempit termasuk organisasi.
Secara umum, cancel culture merujuk pada praktik kolektif untuk menghapuskan eksistensi seseorang dari ruang sosial, karena dianggap melanggar norma atau nilai yang dijunjung mayoritas. Di ruang publik global, fenomena ini sering terlihat dalam bentuk kecaman massal terhadap tokoh-tokoh terkenal karena pernyataan yang dinilai rasis, seksis, atau bertentangan dengan nilai progresif. Dampaknya bisa sangat konkret dalam peristiwa tersebut yaitu kehilangan pekerjaan, kontrak, reputasi, atau dukungan publik. Namun di luar itu, cancel culture juga hidup dalam bentuk yang lebih senyap namun tak kalah melukai karena dia lahir untuk pembungkaman dalam ruang-ruang organisasi.
Ketika kita bicara tentang cancel culture dalam organisasi, maka yang dimaksud adalah bentuk eksklusi yang dilakukan secara sistematis terhadap individu yang dianggap “mengganggu stabilitas”. Padahal, seringkali yang disebut “mengganggu” itu bukan karena melakukan pelanggaran etik, melainkan karena mereka memilih bersuara berbeda, membawa ide-ide baru, atau mempertanyakan struktur yang stagnan. Dalam ruang organisasi yang seharusnya menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan membangun peradaban berpikir, justru terjadi represi terhadap dinamika intelektual.
Secara sosiologis, organisasi diposisikan sebagai miniatur masyarakat. Di sinilah individu belajar tentang struktur sosial, manajemen konflik, dan pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks mahasiswa, misalnya, organisasi kerap menjadi tempat belajar kepemimpinan dan tempat menemukan makna perjuangan kolektif. Namun belakangan ini, banyak organisasi baik kemahasiswaan, keagamaan, maupun sosial-politik justru menjelma menjadi institusi yang anti kritik, menolak dialektika, dan membatasi ruang gerak anggotanya yang tidak konformis. Cancel culture dalam organisasi bukan sekadar peristiwa personal, melainkan tanda bahwa organisasi tersebut sedang mengalami krisis budaya musyawarah dan kepemimpinan.
Fenomena ini semakin terlihat sangat jelas ketika proses “pencabutan hak sosial” dilakukan secara sistemik. Dimulai dari pengucilan sosial, diikuti tidak diberi ruang bicara dalam forum, hingga tidak dilibatkan dalam program kerja. Bahkan tak jarang diakhiri dengan pencabutan jabatan, baik secara langsung maupun melalui tekanan tidak kasatmata. Yang paling mengerikan adalah ketika semua itu terjadi tanpa mekanisme resmi. Tidak ada surat teguran, tidak ada forum klarifikasi, tidak ada prosedur etik yang dilalui. Yang ada hanya sunyi: individu tersebut tiba-tiba hilang dari orbit organisasi tanpa penjelasan yang jujur.
Ada empat ciri khas cancel culture dalam organisasi yang bisa kita temui. Pertama, ia terjadi dalam lingkup terbatas namun dengan dampak personal yang mendalam. Kedua, pelakunya adalah orang-orang dalam, yang memiliki akses terhadap sistem atau kekuasaan, sehingga korban sulit membela diri. Ketiga, motifnya seringkali bukan etik, melainkan politis atau bahkan emosional menjaga kekuasaan, menghindari kritik, atau merasa terancam oleh potensi orang lain. Keempat, cancel culture dilakukan dengan cara tidak langsung, melalui pengucilan sosial dan pemutusan akses, bukan melalui prosedur formal yang transparan.
Jika fenomena ini dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada ekosistem organisasi secara keseluruhan karena cancel culture membunuh nalar kritis. Ketika suara berbeda tidak diberi ruang, maka organisasi kehilangan daya inovatifnya. Pemikiran yang muncul hanya yang sesuai dengan arah kekuasaan, bukan yang benar-benar dibutuhkan untuk perubahan. Kemudian, praktik ini merusak iklim partisipatif pergerakan organisasi karena Anggota menjadi takut berpendapat. Kritik akan diartikan sebagai pemberontakan dan mereka yang melakukan kritik dianggap sebagai pasukan perusak jalan organisasi. Pada akhirnya, cancel culture menciptakan kultur otoritarian dalam organisasi, Kekuasaan dijalankan tidak dengan pertanggungjawaban, tapi dengan pengendalian melalui eksklusi sosial.
Yang lebih ironis, cancel culture seringkali dibungkus dalam retorika moral. “Demi menjaga stabilitas organisasi”, “demi soliditas tim”, atau “demi kepentingan bersama”padahal esensinya adalah ketakutan pada perbedaan. Dalam banyak kasus, individu yang dikorbankan adalah mereka yang paling jujur, paling berani, dan paling progresif. Karena keberanian mereka mengganggu kenyamanan struktur yang mapan.
Maka dari itu, penting untuk mereformasi paradigma organisasi. Cancel culture tidak bisa dilawan hanya dengan retorika toleransi atau slogan keberagaman. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk membangun sistem yang adil dan terbuka. Pertama, organisasi harus memiliki mekanisme klarifikasi yang adil. Tidak semua konflik harus berujung pada eksklusi. Banyak yang bisa diselesaikan dengan dialog terbuka, forum evaluasi, atau musyawarah internal. Kedua, penting untuk membangun budaya konfirmasi, bukan asumsi. Seringkali seseorang “dihilangkan” bukan karena fakta, tetapi karena persepsi yang disebar secara sepihak. Ketiga, struktur organisasi harus menjamin rotasi kekuasaan, agar tidak ada personalisme yang terlalu dominan.
Lebih jauh, organisasi perlu menumbuhkan keberanian untuk berbeda. Perbedaan tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan. Kritik adalah bentuk cinta, bukan bentuk pengkhianatan. Maka mereka yang bersuara kritis seharusnya dirangkul, bukan diusir. Dalam konteks keagamaan atau ideologis seperti organisasi mahasiswa, cancel culture bisa menjadi pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang mereka junjung. Ketika organisasi berbasis moral justru melahirkan eksklusi, maka harus ada perenungan mendalam apakah organisasi ini masih sejalan dengan prinsip-prinsip keadaban yang diajarkannya?
Cancel culture adalah cermin dari krisis kepemimpinan. Ia menunjukkan bahwa para pemegang kekuasaan lebih memilih pembungkaman daripada transformasi. Mereka tidak percaya bahwa kekuasaan bisa dibagi. Mereka takut bahwa pemikiran baru akan mengguncang kenyamanan mereka. Padahal, tanpa pembaruan, organisasi hanya akan jadi mesin rutinitas yang kehilangan arah.
Maka dari itu saatnya kita membangun organisasi yang sehat. Organisasi yang tidak alergi pada kritik. Organisasi yang merawat keberagaman gagasan. Organisasi yang menjadikan keberanian berpikir sebagai aset, bukan ancaman. Hanya dengan cara itu, kita bisa melahirkan generasi pemimpin yang bukan hanya cerdas secara teknis, tetapi juga dewasa secara moral dan tangguh dalam integritas. Karena pada akhirnya, organisasi yang baik bukanlah organisasi yang steril dari konflik. Tapi organisasi yang mampu memeluk konflik sebagai bagian dari pertumbuhan. Dan cancel culture adalah antitesis dari pertumbuhan itu.